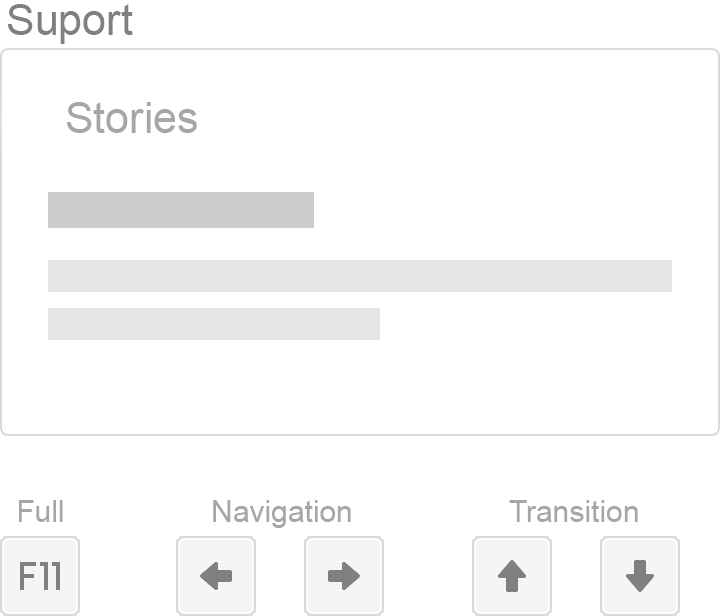Update
Entah memang hoki tahunanku sudah benar-benar habis, atau aku kurang khusyuk berdoa, tapi lelaki itu benar- benar muncul di hadapanku.
Kali ini dia mengenakan kemeja warna putih dengan bordiran Tom Ford di bagian sakunya, dipadukan dengan celana jins abu- abu. Rambutnya ditata menggunakan gel. Entah berapa banyak yang dibutuhkannya untuk menahan rambutnya yang meskipun pendek tapi kelihatannya lebat dan tebal banget itu.
Di pergelangan tangannya masih melingkar Tag Heuer yang menyilaukan itu. Kakinya dibungkus sepasang Nike Air Jordan hitam. Aku sempat melihat kekagetan di sepasang matanya. Tapi dia diam saja.
"Ini Ethan. Residen Obgyn di HJ Intimedika." Galih memperkenalkan.
"Ethan Arkachandra?" sambut Agnia dengan alis terangkat tinggi, pertanda dia lagi antusias. " SMA Widya Nusantara?" tanyanya bersemangat.
"Dhe, bukannya dulu di sekolah lo deket sama Ethan?" Agni mengarahkan tatapannya padaku.
"Kalian saling kenal?" Galih menyela. Tetapi matanya mengamati meja makan dengan penuh minat.
"Mas ganti baju dulu kali." Agnia menghentikan niat suaminya untuk langsung menyerbu makanan. "Main tancap gas aja. Banyak kuman tuh!"
"Iya, iya." Galih menyahut kalem. "Kamu temenin Mas nggak? Masa Dhea nggak berani ditinggal sendirian di sini?" tanya Galih seraya mengerling ke arah istrinya penuh janji. Aku yang menonton adegan itu merasa hampir overdosis. Galih dan Agnia kelihatan bahagia banget. Membuatku jadi bertanya-tanya, akankah aku menemukan pasangan hidup seperti Agnia menemukan Galih?
Ataukah seumur hidup aku akan terus berurusan dengan pria- pria yang lebih memilih perempuan lain dan bukannya aku?
"Ya udah ayo aku temenin ..." Dhea akhirnya bangkit dari kursi. Meninggalkanku hanya berdua dengan si Setan Belang ini. "Dhe, gue tinggal bentar ya?" pamit Agnia.
Perempuan itu bangkit. Galih mengamati setiap pergerakan istrinya dengan penuh pemujaan. Seolah-olah, apa saja yang dilakukan oleh Agnia selalu menarik bagi pria berkacamata itu. Galih kemudian menggandeng istrinya meninggalkan teras belakang tempat makan malam itu dibiarkan menunggu.
Kini yang tersisa hanyalah keheningan yang membalut. Aku tetap duduk di bangku. Sementara Ethan memilih untuk tetap berdiri di ambang pintu.
Aku lebih baik mengerjakan neraca keuangan atau laporan pajak tahunan kantor, ketimbang menghadapi situasi yang serbacanggung saat ini.
Dia yang biasanya menatapku dengan sorot geli dan jenaka, saat ini lebih memilih mengutak-atik ponselnya. Mungkin baginya, benda mati jauh lebih menarik ketimbang yang bernapas dan bikin jengkel seperti aku.
Mungkinkah dia sakit hati dengan perkataanku di restoran tadi? Atau apa? Aku sama sekali nggak mengerti. Aku nggak punya clue, mengapa dia bisa mendadak berubah sikap secara drastis di hadapanku?
Agnia sama Galih di mana sih? Masa ganti baju saja lama banget! Jangan- jangan Galih sekalian nengokin anaknya! Bangke bener!
****
Aku baru sampai di rumah ketika jarum jam menunjukkan pukul setengah sembilan malam. Dan rumahku masih terang- benderang serta banyak motor dan mobil yang parkir di jalanan depan rumah.
Terletak di kompleks terbuka, lingkungan perumahan yang kutinggali selama 29 tahun ini jadi mirip perkampungan. Di seberang rumahku, toko Amin, yang adalah agen sembako. Tempat itu tutup pada jam sepuluh.
Karena mobil nggak bisa masuk, terpaksa aku menitipkan mobil di depan agen sembako itu. "Pak Muji, aku nitip mobil bentar, ya! Nggak apa- apa, kan?"
"Oh, ya. Nggak apa- apa." Sahut Pak Muji yang adalah pensiunan kepala administrasi gudang di pabrik plastik. "Tumben jam segini baru pulang, Neng Dhea?"
"Iya nih. Baru nengokin temen di Mayestik sana."
Pak Muji manggut- manggut. Dulu, semasa masih menjadi kepala administrasi gudang pabrik plastik, pria yang punya empat anak itu jarang sekali berada di rumah. Saking jarangnya, Bu Uci, istrinya sampai memilih pulang kampung ke Garut bersama anak- anaknya. Rumah di depanku ini dikontrakkan.
Rupanya Pak Muji ngekos di sekitar tempat kerjanya. Sementara Bu Uci akhirnya kerja jadi buruh migran ke Hong Kong. Aku nggak tahu pastinya bagaimana. Yang jelas, sebelas tahun yang lalu mereka kembali menempati rumah di seberang rumahku itu. Bagian depannya diubah menjadi toko.
Dari keempat anak Pak Muji dan Bu Uci, hanya Farhana yang masih tinggal ikut mereka. Ketiga kakaknya sudah menikah dan tinggal terpisah dari kedua orangtuanya. Tapi belakangan, Farhana juga jarang muncul.
Kulangkahkan kaki dengan lesu ke dalam rumah. Ada Bu Wiwik, tetangga depan kompleks yang datang bersama suaminya, Pak Mukmin. Lalu Bu Laila yang datang bersama Pak Robi, yang juga seorang polisi. Nilam terlihat mengantarkan nampan berisi gorengan. Tadi pagi dia memang berencana untuk bikin pastel sama lumpia mini. "Lha ini, Dhea baru pulang. Ngelembur, Dhe?" tanya Bu Wiwik yang juga guruku semasa SD itu.
"Iya, Bu." Aku menghampiri orang- orang yang duduk di kursi tamu itu. Kusalami satu- persatu.
"Wah, kamu sudah besar begini kenapa masih sendiri?" tanya Bu Laila. Dia seorang perawat di rumah sakit umum berusia awal lima puluhan. "Itu Mita saja sudah punya anak satu loh, Dhe. Padahal kalian sepantaran toh?"
Aku meringis. Sebenarnya, Bu Laila ini baik. Setiap lebaran rumahku selalu dikirimi opor buatannya yang melegenda di kalangan kompleks ini. Tapi untuk masalah ceriwisnya itu aku angkat tangan.
Beliau sendiri punya lima anak. Tiga mengikuti jejak bapaknya sebagai polisi, satu jadi perawat, dan satu lagi pegawai bank.
Aku lumayan akrab dengan Leli yang kerja di bank. Dia si bungsu yang menyenangkan. "Atau kamu sama si Rino saja?" dia mulai menawar- nawarkan anak nomor duanya yang tiga tahun lebih tua dariku. "Dia mau dipromosikan jadi Kapolsek, loh."
Lagi, aku cuma bisa meringis. Aku melempar lirikan pada ayahku yang hanya manggut-manggut sambil merem. Aku nggak pernah tahu apa yang ada di dalam pikiran lelaki yang membesarkanku itu. Selama ini, belum pernah sekalipun beliau menanyakan kapan aku menikah. Tapi kalau aku lagi "diserang" orang kayak sekarang ini, ayah juga nggak pernah maju membela.
"Kalo bisa jadi kan ya Alhamdulillah ya, Pak Rosyid? kita bisa besanan."
"Wah, dulu saya sama Mas Rino nggak pernah akur, Bu."
"Wooo, kamu masih marah karena dulu Rino pernah ngangkat kamu ke pohon mangganya Pak Sujak? Kamu nggak bisa turun dan nangis ya?"
Tawaku kupaksa keluar. Memang dulu Rino dan Rendi adiknya itu iseng banget. Aku sering menjuluki mereka sebagai anak setan, yang lalu mulutku ditampar sama ibu. Katanya aku nggak sopan ngatain anak orang sebagai anak setan. Sebab secara nggak langsung, aku jadi mengatai ibu bapak Rino dan Rendi adalah setan.
"Ya udah, Oom, Tante, saya permisi dulu. Mau bersih- bersih dan nengok ponakan."
"Nah kan?" sambar Bu Laila lagi. "Coba kalau sudah nikah kan kamu jadi bisa bikin bayi sendiri," lalu menoleh ke Bu Wiwik. "iya toh, Mbak Wik?"
Bu Wiwik untungnya hanya tersenyum.
***
Setelah mandi dan memakai piyama, aku pun masuk ke kamar Mita yang kini menempati kamar tamu. Ayah tentu saja melarang menantu kesayangannya itu untuk bolak - balik naik tangga ke lantai dua.
Kamar tamu sendiri berada di seberang kamar orangtuaku. Letaknya persis di samping tangga. Nilam menempati bekas kamar Bang Doni, sementara Bu Is tidur di kasur tambahan di kamar tamu itu.
Fatih, bayi lelaki yang kini tengah menyusu pada ibunya itu sedang mengepalkan tangannya. Dia memang lucu. Dan selalu tegang. Kalau kuusik sedikit, pasti langsung marah. Lalu tangisnya menggelegar ke seluruh penjuru rumah hingga merembet ke rumah- rumah tetangga.
Bu Is tengah melipat kain bedong, baju- baju bayi, serta popok kain. Ibunya Mita itu berkeras bahwa selama belum menginjak usia tiga bulan, Dek Fatih nggak boleh pakai diaper new born. "Nggak baik buat kulit bayi." Begitu kata beliau.
Tapi Mita sih enak ya. Punya anak dan masih punya ibu yang bisa mengarahkan dan bantu untuk menjaga anaknya. Aku jadi mengkhawatirkan nasibku sendiri di masa depan.
Kalau nantinya aku menikah dan punya anak, siapa yang bakalan mengajariku cara merawat bayi yang baik dan benar. Mertua? Kebanyakan dari mereka itu malah bakalan nyinyirin menantunya. Menganggap bahwa sang menantu nggak mempunyai naluri keibuan.
Meski kerap kudengar Mita saling berbantah dengan Bu Is, namun aku yakin seratus persen bahwa ibu kandung adalah guru dan teman yang paling baik. Hiks. Aku jadi iri.
Melihatku yang berdiri di ambang pintu membuat iparku itu was- was. Matanya langsung mendelik tajam. Maklum, kadang aku memang suka iseng gangguin anaknya. Dia mengacungkan tinjunya ke arahku. Sementara Bu Is gantian memelototi putrinya. "Ulah kitu atuh, Neng. Masa sama ipar teh kamu galak begitu. Biar gimana juga Neng Dhea yang berjasa nemuin kamu sama A' Doni. Kudu hormat sama ipar teh."
Bu Is memang jos gandos!
Rasanya aku pengin ketawa ngakak saat ini. Dan kalau dipikir-pikir, ini adalah hiburan pertamaku hari ini. Melihat Mita mati kutu!
Rasanya aku pengin joget pakai lagu Blackpink yang Ddudududu itu.
*****