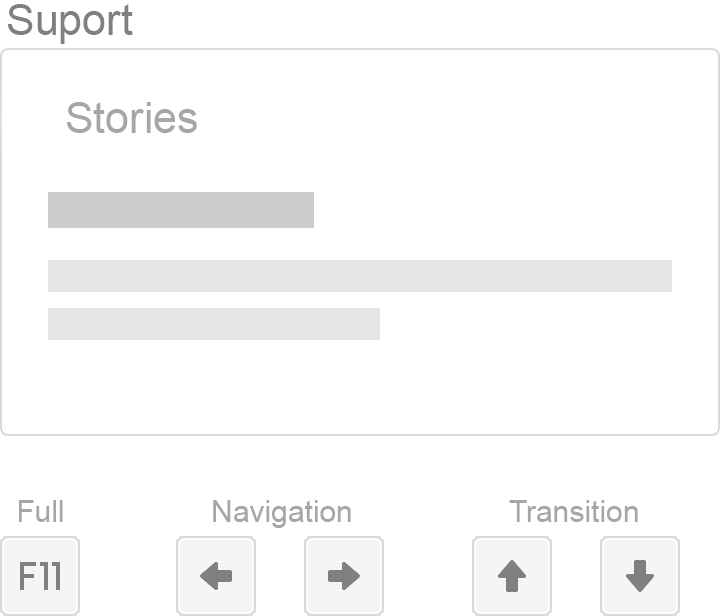Update
"Kenapa tadi nggak nungguin aku?"
"Kamu kayaknya tadi lagi asyik ketawa- ketawa sama perempuan."
"Tapi kalau tahu ada kamu datang kan aku pasti nyamperin."
"Belakangan kamu juga nggak pernah hubungin aku gitu. Minta maaf kek, apa kek."
"Aku sibuk."
"Iya. Kamu sibuk. Dan aku nggak penting!"
"Dhea, please." Ia memohon. Wajahnya terlihat begitu penat. Aku tahu, seharusnya aku menghentikan ini segera. Tapi kayaknya jiwa perangku lagi membara. Nggak bisa dipadamkan begitu saja.
"Kayak gini yang bikin aku menunda hubungin kamu. Aku nggak mau ribut - ribut. Itu cuma perkara kecil. Kita jarang ketemu. Sekalinya ketemu ribut begini."
"Ya!" suaraku hampir pecah. Aku rasanya mau kabur ke kamar supaya bisa nangis. Padahal sebelum-sebelumnya aku belum pernah nangisin cowok. "Memang yang salah di sini. Kamu yang bener!"
"God! Dhea... " Ethan hampir- hampir menggeram. Ia menyugar rambutnya yang sudah lepek. Sebenarnya aku kasihan sama dia. Tapi kan sekarang kami ceritanya lagi berantem. Aku tengsin dong kalau disuruh ngalah duluan. Orang dia yang mulai.
"Sekarang kamu maunya gimana?"
Suaranya saat menanyakan hal itu benar-benar lembut banget. Sampai- sampai aku nggak tega untuk marah lebih lama lagi lalu minta maaf padanya dan mengakhiri pertengkaran konyol ini. Tapi rasa egoisku rupanya sedang meronta- ronta.
Aku maunya dia itu minta maaf duluan padaku. Aku pasti luluh kok kalau dirayu lebih keras lagi. Pada dasarnya cewek kan memang suka dirayu. Meski pun aku mandiri dan dewasa, tapi aku juga butuh dirayu, dibujuk, dan diyakinkan.
Tapi dia tidak bersuara lagi. Kami hanya saling diam di teras rumahku yang remang- remang. "Ya sudah, kayaknya kamu memang lagi emosi. Nggak bisa diajak buat mikir jernih. " Ujarnya kemudian. Suaranya sudah mirip orang kalah perang.
Sejujurnya aku merasa nggak enak hati. Dia kelihatannya sudah penat banget. Tapi aku malah ngajak dia perang kayak gini. Padahal seharusnya aku ngasih dia ketenangan atau kedamaian yang biasanya dikasih perempuan ke pasangannya.
Tapi beginilah yang terjadi. Malam itu, Ethan pulang dengan wajah muram. Meninggalkan sisa pertengkaran di antara kami.
***
"Mungkin karena lo terlalu lama mandiri. Terlalu lama asyik sendiri. Jadi, sewaktu punya pasangan, lo tetap susah buat ngalah." Komentar Kalyana, sewaktu kami bertiga, Kalyana, Valyra dan aku pergi makan siang bareng ke rumah makan khas Manado halal.
Kami memesan nasi, cakalang fufu, bakwan jagung sebesar telapak tangan Mike Tyson, dan Panada isi cakalang.
Aku tercenung mendengarkan penuturan Kalyana. Di antara kami berempat, kalau ditambah dengan Davinsha, hanya Kalyana yang punya hubungan paling awet dengan pasangannya. Walau kayaknya dia anti menikah. Hampir dua tahun dia mempertahankan gaya hidup kohabitasi alias tinggal serumah bareng pacarnya yang seorang chef itu.
Kalyana bilang, pacaran jauh lebih mudah ketimbang menikah. Pacaran masih ada jalan mundur. Menikah baginya akan mengikat seluruh kebebasannya.
Aku sama sekali nggak ngerti logika semacam itu. Kalyana setahun lebih tua dariku. Pacarnya, Aidan, berusia 34 tahun. Seharusnya itu adalah usia di mana orang sudah berani berkomitmen. Berani melangkahkan kaki ke dalam institusi bernama pernikahan. Sayangnya, bagi Kalyana, institusi itu nggak terlihat di matanya.
Dia semakin enjoy menjalani hidup dengan cara begitu. Cara yang nggak lazim diambil oleh kebanyakan perempuan Indonesia.
"Kalau dipikir-pikir, " Valyra menyela, "sebenarnya masalahnya kan nggak sepelik itu. Lo cuma mau dia minta maaf. Tapi dia nganggep bahwa nggak ada masalah di antara kalian berdua."
"Bener banget itu kata Val." Kalyana menyahuti. "Laki memang gitu. Masalah besar itu bagi mereka kecil aja. Yang kecil, dianggep nggak ada."
Tapi masa begitu sih? Yang namanya masalah, besar atau kecil kan tetap harus diselesaikan. Meski menurutku yang salah tetap si Ethan sih.
"Sudah sih. Mendingan lo datengin dia duluan. Minta maaf duluan. Semua kesalahan itu bisa dimaafkan asal bukan selingkuh. " Kalyana menasihatiku.
Aku hanya diam saja.
Memangnya yang kulakukan hari Sabtu itu apa? Aku sudah mencoba untuk merendahkan diri dengan datang ke rumah sakit tempat dia jaga. Dan berakhir dengan ini semua. Pertengkaran yang nggak selesai. Hingga siang ini, belum ada satupun chat atau telepon masuk dari Ethan.
Kayak begini aku disuruh ngalah. Aku ogah dong. Tapi kalau harus putus ...
***
Hingga keesokan harinya, Ethan tetap belum menghubungiku. Itu berarti sudah dua hari kami nggak berkomunikasi. Hal itu sempat membuat mood ku berantakan. Pikiranku nggak tenang dan hatiku gelisah. Bekerja pun rasanya sulit untuk berkonsentrasi kalau yang ada di kepalaku cuma pertanyaan mengapa, mengapa, dan mengapa?
Mengapa setelah jadian semuanya malah jadi kacau begini? Kenapa Ethan tidak meneleponku duluan. Mengajak baikan atau apalah.
Well, aku memang mandiri dan sebagainya. Aku suka melakukan dan membereskan pekerjaanku sendiri. Aku lebih nyaman bila nggak bergantung pada orang lain. Akan tetapi, sebagai perempuan, aku juga ingin diperhatikan.
Aku ingin dirayu kalau lagi ngambek begini. Aku ingin Ethan bersikeras meminta supaya kami baikan. Nyanyi sambil main gitar di depan kantor, kek. Berdiri di depan kantor seharian di tengah sinar matahari Jakarta yang garang menyengat demi cintanya padaku kek.
Ah, kuakui aku memang punya pikiran konyol. Kolot pula. Karena masih memegang teguh prinsip bahwa lelaki yang harus maju duluan. Bisa saja kan sekarang aku muncul di salah satu tempat praktik Ethan dan meminta maaf padanya. Bukannya malah menunggu dalam kegalauan nggak berujung seperti ini. Mangkrak di ruanganku. Di mejaku dengan komputer yang terus menampilkan angka-angka. Serta saluran televisi yang berpindah-pindah dari Bloomberg, CNBC, dan sebagainya. Semuanya ini nggak membantu, dan malah bikin aku mau harakiri jadinya.
Untung saat makan siang, Yunita, Dina dan Fitri menggeretku ke tempat makan seafood di mal. Dina bahkan mengeluarkan kata- kata keramat. "Aku yang traktir Mbak Dhea, deh. Kayaknya Mbak lagi suntuk banget tuh. Berantem kan sama pacar? Btw, pacar Mbak Dhea itu kakaknya Shea ya, kan? Duh, cakep banget nggak sih itu orang. Mukanya Jepang banget. Padahal kan Cina ya?"
Tuh, kan. Mendengar Dina ngomong begitu aku balik jadi baper lagi. Kangen lagi. Mellow lagi. Ah, payah. Tahu begini aku sih nggak usah pacaran sama dia. Gila saja. Akhir tahun nanti umurku sudah 29. Tapi agenda galau masih menguasai perasaanku.
"Udah deh, Mbak." Kali ini Yunita yang menyela. "Pacaran trus marahan itu biasa. Gue aja bolak-balik juga gitu. Cowok itu di mana-mana emang nggak ada yang nggak nyebelin. Mereka bilangnya kita ini spesies rumit. Tapi kita nggak bakalan rumit kalau mereka nggak nyebelin. Betul nggak?"
Beuh. Cara ngomongnya si Yunita ini sudah macam pakar percintaan saja. Padahal umur dia itu lebih muda tiga tahun dariku. Ini mungkin saking lamanya aku ngejomlo. Lama banget nggak pacaran. Jadinya malah begini.
"Udah ayok. " Dina meraih tanganku. Menarikku berdiri dan menyeretku beramai-ramai ke luar dari kandangku yang membosankan tapi nyaman itu.
***
Restoran seafood itu terletak di mal kawasan Kebayoran. Saat jam makan siang begini, jangan harap mendapatkan apa yang dinamakan dengan ketenangan. Begitu memasuki restoran, mata kami langsung bergerilya mencari tempat kosong.
Syukurlah nggak perlu mengantri. Kami langsung mendapatkan tempat meski agak di pojok dan jauh dari jangkauan mata. Fitri langsung sprint mengklaim tempat tersebut sebelum didahului orang lain. Kami pun melangkah cepat menuju meja tersebut.
Kami memesan ikan bakar, oseng tauge, oseng kangkung, cumi saus Padang, udang telur asin. Sembari makan, Fitri, Yunita, dan Dina membahas soal selebgram yang akhirnya meluncurkan produk lip tint terbaru.
Aku yang nggak begitu memahami dunia beauty, hanya jadi pendengar setia sambil terus memasukkan makanan ke dalam mulut. Siang ini, entah mengapa aku mendadak jadi rakus sekali.
"Gue pengin coba sih. Siapa tahu aja cocok." Yunita berkata. "Tapi kadang bikin bibir gue kering gitu. Kayak kurang matte aja."
"Lo pakai itu dong, apa namanya ... oh, ya, pakai MAC pasti bagus banget. Gue udah lama pakai itu soalnya. Dan lo liat sendiri kan hasilnya?"
"Ah, lo mah, anak sultan. MAC sekarang berapa, Neng? Bangkrut dong gue. Kan barengan lagi nyicil mobil. Yang lama gue hibahin ke ade gue." Itu suara Yunita.
"Kalau enggak pakai ini aja, Make Over. Itu kan juga bagus."
"Tau nih." Fitri menyahut. "Gue aja pakai Wardah nggak pernah ada masalah kok. Lo aja yang keseringan kena racun TikTok. Keluar produk ini mau nyobain. Keluar produk itu nyobain juga. Nyokap gue tuh sejak dulu cuma pake Purbasari juga baik-baik aja."
"Eh, gue ke toilet dulu ya." Aku akhirnya menyela. Tanpa sadar, aku sudah menghabiskan dua gelas minuman dan sekarang kandung kemihku penuh.
Saat bangkit dari kursi, aku fokus menyelipkan tubuh di antara banyaknya kursi yang penuh oleh pengunjung. Sesi mengosongkan kandung kemih pun selesai. Ketika kembali ke meja, nggak sengaja mataku menangkap sosok yang dua hari ini nggak berhenti kupikirkan.
Ethan sedang berjalan masuk dengan dua orang teman lelakinya. Aku nggak menangkap bahwa di balik tubuhnya yang jangkung, ada dua orang wanita yang berjalan mengekor di belakang mereka. Salah satunya adalah wanita yang kulihat berjalan dengan Ethan di lorong rumah sakit kemarin dulu.
Mereka duduk agak di depan. Dekat pintu masuk. Wanita itu pun seperti sengaja selalu memepet Ethan. Duduk di sebelah lelaki itu. Bahkan ketika pramusaji mengantarkan buku menu, wanita itu sengaja mendekatkan kepalanya ke bahu Ethan. Kemudian terkekeh.
Aku seperti seorang pesakitan menunggu di ujung sini. Mengamati mereka dengan rasa sakit yang merobek-robek dada. Sambil meraba kantung kemejaku, kuambil ponsel dan kuabadikan momen tersebut. Ini menyakiti hatiku. Sungguh. Maka dari itu aku ingin ini segera berakhir.
Mungkin saja Ethan dan aku nggak tercipta untuk satu sama lain. Itu sebabnya mengapa kami nggak dipersatukan sejak dulu- dulu.
Mataku merebak. Kutahan air mata yang hendak meluncur ke pipi. Kemudian memutuskan untuk kembali ke toilet.
***