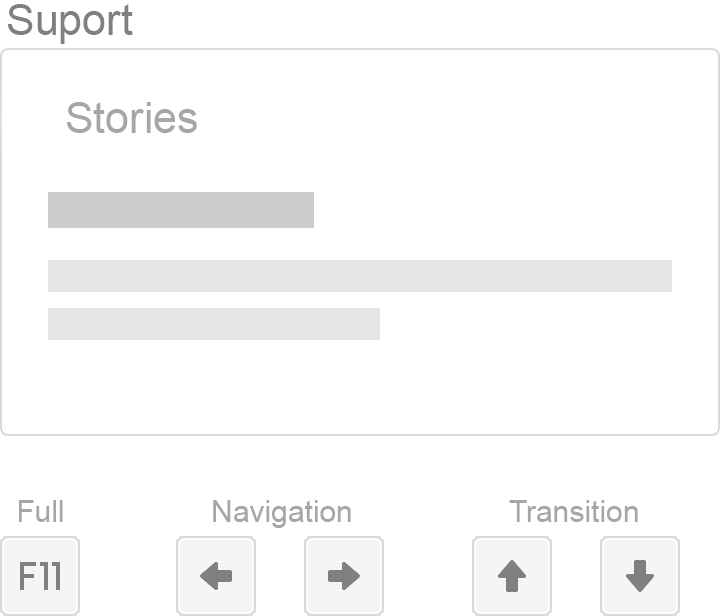Update
Hari berikutnya, aku memang pergi barengan Ewan. Kali ini aku menemaninya untuk belanja oleh- oleh buat keluarganya di Jakarta dan para koleganya di Surabaya. Jadi rencananya lelaki itu akan pulang dulu ke rumahnya di Bulungan sebelum terbang ke Surabaya pada Minggu pagi.
Aku sendiri juga harus mencari oleh- oleh buat keluargaku. Mita belum apa-apa sudah pesan daster yang khusus untuk ibu menyusui. Lalu kacamata hitam. "Sama barang yang lucu- lucu." Ujarnya ketika tahu aku ada di Bali.
Aku memang hanya pamit sama ayahku dan Mbak Asih. Saat itu, Mita sedang pergi bareng Ahsan dan ibunya. Lagi pula aku nggak berangkat dari rumah waktu itu. Melainkan dari kantor saat Jumat sore.
Pagi itu, setelah sarapan di hotel tempat Ewan menginap, kami pergi ke pasar dan menyempatkan diri untuk pergi ke Seminyak.
Aku sempat mampir ke butik- butik pakaian branded. Dan berakhir dengan nggak membeli apa- apa. Rasanya aku akan menangis kalau harus merelakan uang seharga satu skuter matic Benelli hanya untuk membawa sehelai gaun dari butik Balenciaga atau sebuah tas dari butik Gucci.
Harga outfit paling mahal yang ada di lemariku nggak sampai dua juta. Itu pun aku belinya karena kalap. Hanya ingin kelihatan gorgeous, stunning, glowing saat menghadiri pernikahan Mas Wicak empat tahun yang lalu. Dan sekarang pun gaun itu masih ngendon bertapa di dalam lemariku karena jarang kupakai. Karena warna biru mudanya kuanggap nggak sesuai dengan kepribadianku.
"Sebenarnya gue mau kasih tahu lo sesuatu. " Tiba-tiba saja Ewan berujar. Aku seketika mengalihkan pandangan ke arahnya. Menaikkan sebelah als selagi menunggu dia melanjutkan kalimatnya.
"Gue ... gue .... sekarang sebenarnya lagi pedekate sama Tami."
"Tami?" ulangku. "Kayak pernah denger." Ujarku seraya mencoba menggali ingatan tentang sosok bernama Tami ini.
"Ih, ini Jihan Tamira. Yang dulu pernah ikut lomba maraton!"
"Yang item itu?"
"Eh sekarang dia udah glowing tahu! Dia sekarang kerja jadi PR di hotel di Embong Kaliasin, sana." Ewan nyaris bersungut-sungut. Aku hanya manggut-manggut. Setahuku, Tami dulu memang pindah ke Surabaya di tengah- tengah semester ganjil. Ayahnya yang seorang pegawai pajak dipindahtugaskan ke ibukota propinsi Jawa Timur itu.
Dulu Tami memang berkulit gelap. Badannya lencir--- tinggi dan langsing. Dan sebenarnya dia itu punya wajah yang mirip-mirip Prisia Nasution. Manis sih.
"Sekarang juga dia meski nggak putih tetap cantik. Kayaknya kalo kulitnya putih kayak elo jadi nggak pantes. Kayak si Ariana Grande itu. Lebih bagus kan kalo kulit dia tan. Kalau terang nggak pantes aja."
Aku manggut-manggut. Kami kemudian mampir ke warung yang menjual nasi tempong yang sebenarnya bejibun jumlahnya di sini. Padahal itu sebenarnya adalah makanan khas daerah Banyuwangi. Kami memesan dua nasi tempong komplit dan dua gelas jeruk peras dingin.
"Kalo gitu kenapa lo posting foto kita berdua di IG lo? Emang Tami nggak bakal cemburu?"
"Nggak." Ewan tersenyum. Pramusaji mengantarkan makanan dan minuman yang kami pesan. Aroma pedas langsung menusuk hidung. "Secara menurut dia, gue bukan tipe elo. Begitupun dengan sebaliknya."
"Kok dia bisa percaya diri banget gitu ya?" keningku mengernyit. Satu suapan masuk. Dan lidahku rasanya seperti ditendang. Rasa pedas menggigit membuat bibirku memerah. "Siapa tahu kan gue berubah haluan. Mendadak gue naksir lo, misalnya. "
Ewan malah tersedak dan langsung panik meminum jeruk dinginnya. Aku sebenarnya mau ketawa. Tapi kasihan juga melihat Ewan yang sepertinya kesakitan itu. Jadi aku hanya bisa memandanginya. Aku nggak biasa menyentuh sembarang orang. Apalagi lelaki. Jadi aku nggak bangkit dari kursi dan mengelus punggungnya atau apa. Sekarang aku melihat diriku sendiri sebagai sosok yang konyol dan dingin. Hanya ketika pramusaji di warung itu melintas, aku melambai untuk meminta sebotol air mineral dingin.
Muka Ewan memerah. Tapi batuknya mereda setelah pramusaji mengantar sebotol air mineral dan membukanya untuk Ewan. Lelaki itu langsung menandaskan separuh botol. Aku berkata datar. "Sori karena gue nggak ngusap- ngusap punggung elo."
"Jadi lo ini memang dingin ya? Pantes dulu Ethan ragu- ragu mau deketin elo. " Ia bersungut. Mukanya tampak bete.
Pupilku melebar. Aku menatap Ewan lurus-lurus. "Apa maksudnya itu?"
"Emangnya elo enggak ngerasa?" Ia bertanya balik. Kali ini dengan mimik sinis.
Aku bergeming. Tetapi tatapanku tetap lurus ke arahnya. "Yah ... dulu ada gosip. " Ewan garuk-garuk leher. Tampak gelisah. Seolah-olah mau membuka sesuatu rahasia mahapenting yang sudah terpendam bertahun-tahun lamanya. "Apa?" todongku.
"Yah, gosipnya lo .... sama Agnia itu pernah pacaran!"
"Apa!" sontak aku langsung bangkit dari kursi. Melotot lebar ke arah Ewan. Nggak peduli bahwa beberapa orang yang sedang makan di situ menoleh ke arah meja yang kami tempati.
"Siapa yang nyebar gosip terkutuk itu?"
"Siapa lagi? Ya temen lo itu. Si Erlin. "
Napasku memburu. Kenapa Erlin bisa punya imajinasi seliar itu? Aku? Pacaran sama Agnia? Yang benar saja sih?!
"Tadinya gue denger- denger tuh Ethan sempat mau deketin elo. Dia liatnya kan elo tuh deketnya sama Erlin waktu awal-awal masuk SMA. Lo k mana- mana barengan Erlin terus kan selama MOS itu. Erlin menarik perhatian Ethan dengan ngaku kalau dia emang deket sama lo dari SMP. Terus jadinya selain deketin elo secara pribadi, Ethan juga cari tahu tentang lo dari Erlin."
"Tapi kan dia bisa tanya ke Agnia atau siapa kek? Dan elo kok begonya baru ngasih tahu gue sekarang sih?"
"Karena ... Karena ... waktu itu gue juga sempat naksir sama lo."
Aku hampir saja menggebrak meja. Tapi kutahan karena selain nggak mau bikin tontonan, aku juga nggak sudi disuruh ganti rugi kalau sampai ada properti warung ini ada yang rusak.
Aku mengetatkan rahang. Gigi-gigiku bergemetukkan. Saking gemasnya. Kenapa Ewan bisa sebego itu. "Sori." Hanya itu yang dikatakan Ewan. Sementara nafsu makanku sudah menguap.
Aku kesal bukan main. Jadi selama hampir tiga belas tahun ini aku disabotase sama Erlin dan Ewan? Benar- benar itu orang pada.
Kuambil tasku lalu kutinggalkan Ewan tanpa permisi. Dengan dada yang terasa bergolak oleh amarah, aku meninggalkan warung itu. Mencari taksi atau kendaraan apa pun yang bisa mengantarkanku kembali ke apartemen Davinsha. Aku rasanya mau menyurukkan kepala di bawah bantal. Dan tidur selama seribu abad. Supaya bangun- bangun nanti aku sudah hilang ingatan.
***
Aku nggak jadi menyurukkan kepala ke bawah bantal dan tidur selama seribu abad. Yang kulakukan akhirnya hanya duduk di sofa di depan televisi dengan seliter es krim rasa matcha. Dan ini adalah tipikal matcha yang kayak rumput gitu rasanya. Manisnya sedikit banget. Ih, kok ada ya orang yang mau beli beginian. Lebih parah lagi, aku yang nyaris menghabiskan es krim tersebut. Kalau Davinsha nyariin biar kuganti deh.
Saat ini aku lagi menumpahkan kekesalan dengan menikmati film-film lawas dari tv kabel yang kebetulan menayangkan 27 Dresses, 13 Going to 30 . Katherine Heigl dan Jennifer Garner mencoba menemukan cinta sejatinya melalui jalan berliku. Katherine yang sebenarnya naksir si bos, eh si bos malah diembat sama adiknya. Sementara Jennifer Garner yang baru menyadari bahwa dirinya mencintai teman masa kecilnya yang diperankan oleh Mark Rufallo. Sayangnya Mark sudah bertunangan dengan perempuan lain.
Cinta. Pernahkah aku benar-benar jatuh cinta? Cinta pertamaku kandas. Harus kuakui orang itu adalah Ethan. Kalau saja waktu itu Ethan nggak mencari tahu tentang aku lewat Erlin, tapi lewat teman-teman sekelasku seperti Agni, Rania, atau Dara, pasti kejadiannya nggak bakalan begini.
Akan tetapi, kalau dari dulu-dulu aku sudah jadian sama Ethan, apakah saat ini kami akan dipertemukan dengan jalan begini? Kemungkinan besar Ethan dan aku memang akan jadian. Tapi bisa saja kami putus di tengah jalan. Dan sampai sekarang, kemungkinan kami juga bakalan memusuhi satu sama lain.
Sekarang ini, kondisi hubungan kami memang nggak lebih baik. Tapi saat ini sepertinya kami sedang memulai sebuah hubungan yang sama sekali baru.
Ethan memang kelihatan banget lagi mendekatiku. Tapi aku memang nggak bisa geer begitu saja. Siapa tahu sebenarnya dia cuma penasaran. Mungkin saja lelaki itu hanya ingin tahu bagaimana rasanya dekat denganku. Aradhea Puspitha yang jutek, galak dan dingin.
****
Sisa liburanku kugunakan untuk bermalas- malasan. Terkadang tidur sampai tengah hari, terkadang makan di luar bareng Davinsha. Kumpul- kumpul bareng anak- anak Ranjana Denpasar, atau ke pantai- pantai yang ada di Bali sampai ke Nusa Penida, Danau Batur, dan Ubud.
Pada hari terakhir, kulitku berubah jadi hitam keling. Tapi aku happy. Ewan sudah kembali ke Jakarta dan meninggalkan sekotak cokelat serta oleh-oleh sebagai permintaan maaf di concierge apartemen yang Davinsha dan aku huni.
Sementara sejauh ini, Ethan sudah berhenti menggangguku. Rasanya memang sepi. Semacam ada yang mengganjal. Biasanya kalau sudah kujuteki, lelaki itu pasti balik lagi, balik lagi. Sekarang aku merasa kayak kehilangan banget. Baru kusadari, aku memang sudah kena pesona Ethan.
Mita selalu mempromosikan bahwa kalau Ethan naksir diriku, aku seperti ketiban durian runtuh ( Mita memang doyan banget sama durian. Sementara aku enggak).
"Secara Ethan itu orangnya alim banget. Nggak neko- neko." Begitu kata Mita pada suatu hari ketika kakiku keseleo dulu itu.
Aku nggak ngerti, dia bisa punya pendapat kayak begitu itu dari mana. Berdasarkan apa. Padahal dia sama Ethan juga baru kenal.
"Ah, kalau lo cuma ngeliatin berdasarkan muka dia yang innocent begitu sih, mana valid? Siapa yang tahu kalau muka dia doang yang innocent. Ternyata kelakuannya parah." Bantahku yang waktu itu nggak rela kalau ada yang memuji-muji dia.
Sebelum berangkat ke bandara, Davinsha kembali membawaku ke toko oleh-oleh. Dia membelikanku beberapa macam penganan seperti cokelat, pie susu, dan masih banyak lagi. Lalu ada kaus berwarna putih polos dengan tulisan- tulisan I Love Bali dan sebagainya. Dia juga membelikanku beberapa potong pakaian dan produk perawatan wajah dan tubuh disertai pesan- pesan sponsor. "Lo boleh patah hati. Tapi nesti tetap cantik dan glowing. Biar kata jomlo kalau cakep orang yang nyakitin lo pasti bakalan nyesel deh."
Waktu berangkat aku hanya membawa satu koper dan ransel. Kini pulangnya aku membawa dua koper ukuran besar, satu travel bag, dan ransel.
Penerbanganku sekitar jam tiga sore. Aku juga berpesan pada Davinsha supaya kapan- kapan mengunjungiku ke Jakarta. Nggak usah peduliin sama si Giri brengsek itu. Dia cuma nyengir.
Selama aku berada di Bali, Davinsha juga nggak pernah kelihatan pergi berdua dengan lelaki tertentu. Pasti perginya ramai- ramai. Memang kamu punya prinsip yang sebangun. Kalau patah hati nggak langsung nemplok ke pelukan cowok lain. Itu sama dengan murahan.
**
Aku sampai di Cengkareng sekitar pukul setengah lima. Rencananya, aku minta jemput Syahid. Untuk saat ini dia yang paling aman. Hubungan kami meski telah terjalin hampir lima tahun tetap nggak ada percikan asmara antara dia dan aku.
Tapi ketika aku turun dari pesawat kemudian pergi ke tempat penarikan bagasi, lalu berjalan ke luar sambil kepayahan menyeret dua koper yang siatasnya kutumpangi travel bag, bukan sosok datar muka bosan Syahid dalam balutan jaket hitam andalannya itu. Melainkan sosok lain yang tampak menjulang dan harus kuakui tampak ganteng banget kali ini--- mungkin ini efek dari sudah sepuluh hari nggak ketemu--- dalam balutan jaket bomber abu- abu besi dan celana chino warna senada serta sepatu Adidas hitam.
Aku mematung saat tatapan kami bertemu. Dia kemudian menghampiriku dengan langkah pasti. Kedua tangannya tersembunyi di saku jaketnya. Sekarang ia menjulang di hadapanku. Tanpa senyum. Hanya matanya yang melekat ke mataku. "Udah seneng- senengnya?"
Aku hanya bisa membisu. Nggak mampu mengeluarkan kata- kata yang sudah kususun cermat di dalam kepala. Tangannya kemudian meraih pegangan koper, sementara tangan yang satunya lagi meraih dan menggenggam tanganku. Erat. Hangat. Nyaman.
Dan aku tetap nggak mengerti arti dari semuanya ini. Karena pada dasarnya, aku ini bego kalau sudah berurusan dengan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan asmara.
***
Ini konfliknya nyaris nggak ada ya... hehehe....