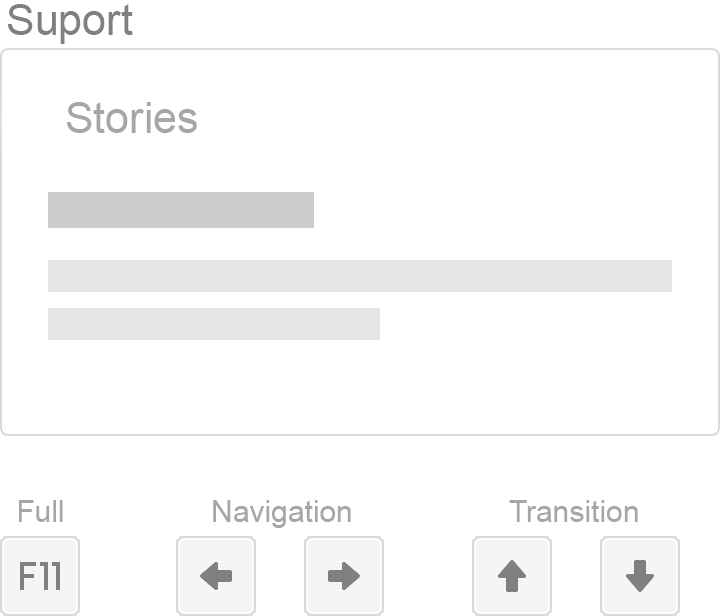Update
Samar-samar, aku dapat menghirup aroma citrus. Juga sebuah tangan yang nggak berhenti untuk mengelus kepalaku. Kepalaku rasanya masih sangat pening. Aku nggak tahu apa yang terjadi padaku. Selama ini aku nggak pernah sok-sokan skip makan juga. Jadi nggak mungkin aku kena tipus kan?
Lagi pula aku tergolong jarang pingsan. Seumur hidupku yang sudah menginjak angka 29 akhir tahun nanti, aku hanya pernah pingsan dua kali. Waktu pertama kali mendapatkan menstruasi karena aku kaget banget darah bisa keluar dari ituku. Takut aku mati kehabisan darah. Yah, aku pernah mendapatkan edukasi dari ibu. Tapi tetap saja nggak menyangka kalau darah bisa keluar dari situ. Mana jumlahnya banyak dan kerap disertai rasa nggak nyaman. Atau kram perut.
Kejadian kedua adalah ketika ibuku meninggal. Aku seperti merasakan duniaku runtuh waktu itu. Aku yang manja dan bandel berpikir nggak bakalan bisa hidup tanpa ibu. Dan hari ini aku mendapatkan pengalaman pingsan untuk ketiga kalinya. Dan itu ... entahlah. Aku sendiri juga nggak tahu penyebabnya apa. Yang jelas mendadak kepalaku terasa ringan melayang. Lalu semuanya gelap.
"Dhea..." Aku hafal mati dengan suara itu. Milik lelaki yang dua mingguan ini berusaha kuenyahkan dari kepala. Berusaha kulupakan walau rasanya berat. Aku sudah terbiasa dengan keberadaan dan perhatian Ethan sebelumnya. Jadi perlakuannya terhadapku belakangan ini memang membuatku sakit hati.
"Dhea, ini aku... " Suara itu seperti menarik kesadaranku. Perlahan, kelopak mataku terbuka. Mengerjap-ngerjap. Menyesuaikan dengan cahaya putih yang menerangi ruangan berbau steril ini. "Hei, kamu udah bangun." Ethan membawa tanganku ke bibirnya, kemudian mengecupnya dengan raut wajahnya yang nggak kalah pucat dengan milikku. Dia tampak gelisah. "Tekanan darah kamu kok bisa cuma segitu? 80/70. Kamu ngapain saja?"
Aku tahu dia khawatir. Karena aku bisa merasakan kegelisahannya dari nada bicaranya. Dari pupilnya yang terus-menerus bergerak-gerak. Pertanda bila lelaki itu sedang gelisah. "Kamu pasti forsir kerjaan kan?"
"Gimana keadaan Hanna?"
"Bayinya baik. Walau sebetulnya belum waktunya keluar. Jadi bobotnya hanya 2,2 kilogram."
Kurasakan sapuan kegelisahan kembali menyelimuti benak. Aku turut sedih untuk Hanna. Dia sudah berkorban begitu banyak untuk Gilda. Tapi ganjaran yang harus diterima begitu berat. "Kamu berdoa saja supaya Hanna selamat."
"Trus kenapa kamu ada di sini?"
"Ini ruanganku." Dia mengumumkan dengan wajah sedikit sombong. "Aku masih di kafe rumah sakit tadi sewaktu mengirim pesan singkat ke ponselmu. Lalu dapat panggilan darurat dari operator OSA. Karena pasien yang mereka bawa mengatakan kalau dokternya adalah dokter Zora. Sementara beliau sedang ke London untuk menengok saudaranya."
Aku hanya tercenung mendengarkan penjelasannya. "Lelaki itu apa dia ..."
"Bukan." Sahutku tawar. "Bayi yang dikandung Hanna memang punya Erik. Tapi itu bukan punya mereka. Erik nikah sama Gilda. Sepupu Hanna. Singkat kata itu adalah bayi Erik dan Gilda."
"Hanna sudah terkena gejala pre-eklampsia. Kadar albumin dalam urinenya sudah plus dua. Tensinya juga tergolong tinggi. 150/130. Untung pihak OSA berhasil menstabilkan kondisinya. Waktu sampai di meja operasi, tensinya sudah normal walau cenderung tinggi. Tapi kami harus segera mengeluarkan janinnya."
Aku masih terdiam dan mencerna kata-kata Ethan barusan. Dia masih menggenggam erat tanganku seolah- olah takut kalau-kalau aku kabur. Ada rasa was-was yang terpancar dari sepasang matanya yang gelap.
Lain dengan Shea yang warna matanya cokelat terang, warna mata Ethan cenderung lebih gelap. Mungkin ada keturunan dari pihak papanya.
Tanpa kusadari, mataku sudah menatapnya. Pandangan kami bertemu. "Dhea, aku benar-benar minta maaf."
"Buat apa?"
"Buat semuanya."
"Lalu?"
"Aku pengin tetap sama kamu."
"Tapi kulihat kemarin kamu nyaman-nyaman aja dicium sama perempuan itu."
"Retna maksud kamu?" dia bertanya panik. Lalu mendesah. "Well, kalau ini bisa bikin kamu lega, Retna memang suka sama aku sejak lama. Kami teman kuliah. Tapi aku nggak pernah punya perasaan apapun ke dia."
"Kenapa? Dia cakep. Dia dokter. Pasti lebih ngerti kamu ketimbang aku yang cuma ngurusin duit doang."
"Aku harus gimana lagi jelasinnya ke kamu, Dhea. Waktu hari Jumat itu aku nggak enak badan. Padahal seharusnya giliran aku jaga. Dia bersedia gantiin aku. Aku nggak punya pilihan lain kan? Sebagai timbal baliknya, aku harus nemenin dia ke mal hari Sabtu itu."
Aku menatapnya dengan kosong. "Jalan bareng kamu ternyata risikonya banyak banget ya." Aku akhirnya mencoba untuk bangkit dari posisi tidur. Ethan tetap memegangi tanganku dengan hati-hati, membantuku bangun, seolah-olah aku yang baru saja melahirkan bukannya si Hanna. "Pelan-pelan." Bisiknya khawatir.
Yang kubalas dengan dengusan. "Aku mau pulang."
"Aku anterin ya?"
"Nggak usah. Aku bareng Sivan aja."
"Cowok tadi?" alisnya yang lebat menyatu di glabella. "Dia siapanya kamu? Bukan pacar kan? Aku belum setuju putus sama kamu waktu itu."
Aku menghadiahinya tatapan menghunus. "Maksudnya kamu ngomong gitu itu apa? Kamu yang nggak pernah hubungin aku kan. Sampai aku liat kamu makan siang bareng teman-temanmu di mal. Sama cewek itu juga. Padahal sebelumnya kita berantem. Tapi kamu nggak ada itikad buat hubungin aku."
" Karena kamu masih panas waktu itu."
"Ya kamu bujukin aku dong. Namanya aku pacar kamu! Masa marah dibiarin aja! Kamu ini kurang berjuang tahu nggak!"
"Aku kurang berjuang?" giliran matanya yang membelalak. "Kamu tahu gimana getolnya aku deketin kamu, Dhe. Kamu yang jutek, cuek, galak. Tapi aku nggak pergi. Karena aku betul-betul mau kamu. Kenapa kamu nggak paham juga."
"Karena setelah jadian, setelah kamu ngumbar kata-kata manis ke aku dan segalanya itu, komunikasi kita kayak rusak gitu aja. Kamu jadi jarang hubungin aku. Kita jadi sering berantem. Apa namanya kalau nggak cocok?"
"Jadi menurut kamu kita nggak cocok?" dia menggeleng, seperti nggak habis pikir setelah melepaskan tangannya dariku. "Come on, Dhea, aku nggak pernah menganggap kalau kita nggak cocok. Semua bisa dibicarakan. Retna pasti bakalan ngejauhin aku juga kalau kita udah nikah. Kamu jangan jadi nggak masuk akal gitu dong,"
"Aku?" kuarahkan telunjukku pada diriku sendiri, "nggak masuk akal?" Rasa-rasanya aku emosi. Ingin kuberkata kasar tapi nggak mampu karena nggak terbiasa. Terakhir aku melakukannya mulutku digampar sama Ibu. Palingan aku cuma ngomong "bangke" atau yang nggak terlalu kasar. Lagipula aku menghormati Ethan.
"Sekarang kamu maunya gimana?" Ethan bertanya. Suaranya kali ini lebih tenang setelah sempat meninggi karena adu argumen denganku. "Jangan minta putus. Aku sudah susah payah cari kamu. Aku seneng banget waktu akhirnya kita ketemu. Aku bahagia banget waktu kita jadian. Kamu nggak boleh seenaknya putusin lelaki yang buat dapetin kamu mesti uji nyali."
Mataku menyipit.
"Ini yang aku takutin kalau kita ngomong begini. Buntut- buntutnya kamu pasti putusin aku. Dasar perempuan!"
"Oh kamu mulai sexist?" Nggak terima, aku akhirnya nekat turun dari ranjang periksa. "Terserah kamu mau terima apa enggak keputusanku. Pokoknya aku nggak bisa sama-sama orang yang dengan gampangnya melontarkan komentar berbau gender begitu! Kita putus, Ethan Arkachandra Wishnu Patria Lee!"
Dengan begitu, aku berderap keluar. Membawa kedongkolan yang memenuhi dada. Dasar setan belang!
**
Keesokan harinya aku datang menjenguk Hanna bersama dengan Agnia, Dara, Rissa dan Rania yang kebetulan juga lagi berada di Jakarta.
Kulihat Erik tetap berada di rumah sakit. Ia kelihatan begitu lelah dan kalut. Tapi diam saja. Agnia dan aku berapi-api mendekati lelaki itu. "Sekarang lo puas kan?" aura preman Agnia, keluar. Ia mencoba mengintimidasi Erik, yang sama sekali nggak menanggapi kemarahan Agnia. "Lo dapat anak. Lo nggak perlu ngurusin ibunya yang sekarat."
Tatapan Erik berpindah kepadaku. Ketika menatapnya, aku bisa melihat sebersit penyesalan di matanya. "Kenapa kamu biarin Gilda berbuat begitu sama Hanna, Rik? Kami percaya kamu bakal jagain Hanna. Kami berusaha nggak ikut campur. Tapi ternyata kamu ngecewain kami."
"Sorry, Dhe. Belakangan aku sibuk. Dan Gilda emosi karena kami ketahuan."
Huh. Khas Gilda sekali. Setiap dia tertimpa masalah, selalu harus mencari kambing hitam. Selalu harus ada orang yang bisa dia salah-salahkan.
"Sekarang kamu mau gimana?"
Erik menyugar rambutnya dengan gusar. "I don't know, Dhea." Suaranya goyah. "I don't know."
Dalam hati rasanya aku juga mau menangis. Tapi kutahan-tahan. Aku nggak mungkin mengumbar air mata di tempat umum. Akhirnya aku berjalan menjauh dari ruang ICU tempat Hanna masih belum sadarkan diri. Semuanya terjadi bersamaan. Kacaunya hubunganku dengan Ethan. Musibah yang menimpa Hanna.
Hingga di ujung lorong ICU itu aku menemukan toilet dan berbelok. Aku melepaskan tas selempang dan kuletakkan di atas meja granit di depan cermin raksasa di dalam ruangan bernuansa putih bersih itu. Kedua tanganku kemudian bertumpu pada meja, kepalaku menunduk. Satu persatu air mataku mulai meluncur berjatuhan.
Sebentar kemudian, kurasakan ada sepasang lengan yang membalikkan tubuhku, dan menarikku ke dadanya. Aroma musk dan rempah-rempah langsung menyambutku. Disusul usapan lembut pada rambutku. Dan kecupan ringan di pelipisku. "Jangan nangis sendirian selama masih ada aku, Dhe."
Aku nggak tahu, ternyata meskipun hatiku diliputi amarah yang luar biasa terhadap ketidakjelasan sikap Ethan, namun rindu di dadaku seolah-olah meledak setelah kusimpan dan kuendapkan begitu lama. Aku pun balas mengeratkan pelukanku.
"Aku sayang kamu. Aku mau kamu. Kamu jangan pergi lagi, ya. Aku minta maaf kalau ternyata usahaku kurang buat meredakan amarah kamu. Tapi kamu jangan minta aku buat menjauh dari kamu."
Dan kata-katanya malah membuat air mataku meluncur dengan derasnya.
**